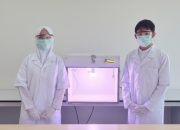Setelah 2–4 hari, telur menetas menjadi larva. Pada fase awal, larva mengonsumsi media fermentasi sebelum diberi pakan utama berupa limbah organik basah seperti sayur, buah busuk, nasi basi, ampas tahu, dan sisa dapur lainnya. Pakan dipotong kecil agar mudah diurai dan diberikan 1–2 kali sehari.
Dalam 14–18 hari, maggot tumbuh menjadi larva dewasa (prepupa) yang berwarna coklat tua dan bergerak lambat. Inilah saat panen, di mana maggot bisa digunakan sebagai pakan ternak atau disisihkan untuk berkembang menjadi lalat dewasa demi menjaga siklus produksi.
Manfaat ekonomi dan ekologi
Selain mengurangi timbunan sampah, budidaya maggot memberi peluang tambahan pendapatan bagi warga. Larva yang dihasilkan dapat dijual sebagai pakan unggas atau ikan, sementara pupuk organik dari sisa penguraian bisa dimanfaatkan untuk pertanian.
“Melalui program ini, masyarakat tidak hanya belajar mengolah sampah, tetapi juga memahami bahwa limbah rumah tangga memiliki nilai. Dari yang awalnya dianggap masalah, bisa menjadi peluang ekonomi dan solusi lingkungan,” tutur Aprila.
Ia berharap, metode ini dapat diadopsi dalam skala lebih besar, seperti di tingkat komunitas, sekolah, atau kelompok tani, sehingga manfaatnya semakin terasa. Menurutnya, inisiatif ini sejalan dengan gerakan hidup berkelanjutan dan Zero Waste yang kian relevan di tengah isu perubahan iklim dan krisis sampah.
Dengan pendekatan yang sederhana, biaya terjangkau, dan dampak yang besar, budidaya maggot berpotensi menjadi solusi permanen bagi persoalan sampah organik di daerah pedesaan maupun perkotaan.